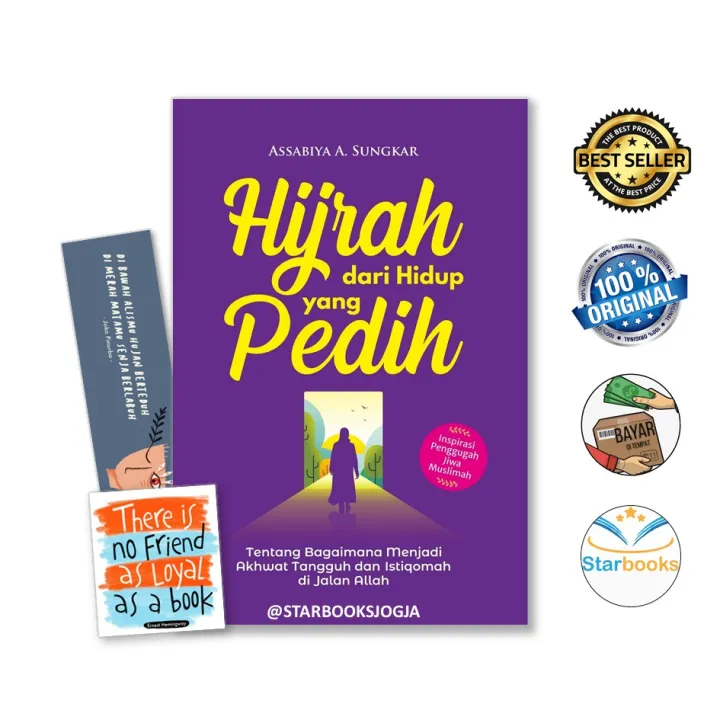Peran Memoar dalam Membongkar Kekerasan Sunyi
PasarModern
Tidak semua kekerasan terdengar dengan suara keras. Sebagian dari mereka justru hadir dalam bentuk yang paling sulit ditolak: perhatian yang terasa menyelamatkan, pujian yang menenangkan, dan janji perlindungan yang tampak seperti cinta.
Ia tidak memaksa, tidak memukul, tidak berteriak. Ia menunggu. Ia mendekat perlahan. Ia membuat korban percaya bahwa kebingungan adalah cinta, bahwa diam adalah bentuk kesetiaan, dan bahwa rasa sakit adalah harga yang wajar untuk “diperhatikan”. Inilah yang membuat grooming begitu berbahaya. Ia bukan sekadar kejahatan, melainkan proses panjang yang merusak dari dalam, menukar kendali dengan rasa aman palsu, dan membentuk luka yang baru terasa bertahun-tahun kemudian.
Grooming bekerja di wilayah yang jarang kita bicarakan: ruang emosional anak dan remaja, ruang sunyi tempat mereka belajar tentang kasih sayang, kepercayaan, dan nilai diri.
Broken Strings dan Kekerasan Sunyi
Memoar Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah karya Aurélie Moeremans membuka ruang sunyi itu tanpa romantisasi. Buku ini bukan kisah tentang sensasi kekerasan, melainkan tentang bagaimana kekerasan bisa hidup bertahun-tahun tanpa disadari sebagai kekerasan.
Aurélie menulis bukan dari posisi orang yang “sudah selesai”, tetapi dari seseorang yang harus menunggu hingga dewasa, hingga mencapai usia yang dulu digunakan untuk menghancurkan hidupnya untuk akhirnya memahami bahwa apa yang ia alami bukan cinta, melainkan kekejaman yang menyamar sebagai kasih. Di titik inilah Broken Strings menjadi lebih dari sekadar memoar personal. Ia menjelma cermin bagi masyarakat yang terlalu sering gagal mengenali grooming, gagal melindungi anak, dan gagal mendengarkan mereka yang bertahan dalam diam.
Buku ini menantang kita untuk bertanya: berapa banyak anak lain yang masih hidup di dalam kebingungan yang sama, sementara kita sibuk menyebutnya “hubungan”, “kedekatan”, atau “urusan pribadi”?
Grooming sebagai Proses Manipulasi Psikologis
Sebagaimana ditekankan berbagai kajian termasuk International Centre for Missing and Exploited Children, grooming adalah proses manipulasi psikologis yang disengaja oleh orang dewasa terhadap anak di bawah 18 tahun untuk membangun kedekatan emosional demi mempermudah eksploitasi seksual.
Proses ini jarang dimulai dengan kekerasan. Ia sering diawali dengan perhatian, teguran yang tampak peduli, atau sikap “melindungi”, lalu berlanjut pada isolasi korban, pengaburan batas, dan penguatan kontrol melalui rasa takut atau rasa bersalah. Pola grooming tampak jelas dalam kasus kekerasan seksual terhadap remaja perempuan 13 tahun di Pantai Tedis, Kota Kupang, pada 14 Januari 2026.
Peristiwa ini kerap dipahami semata sebagai pemerkosaan brutal, padahal melalui kacamata Broken Strings, ia juga menunjukkan mekanisme grooming di ruang publik. Kekerasan bermula dari pendekatan yang tampak wajar: teguran dua pria dewasa dengan dalih keamanan yang sejak awal memuat relasi kuasa berbasis usia dan otoritas. Salah satu pelaku kemudian mengisolasi korban dari temannya, melemahkan batas dan ruang aman untuk menolak. Penolakan korban justru berujung pada kekerasan seksual disertai ancaman pembunuhan, menegaskan bahwa grooming sering menjadi pintu masuk menuju kekerasan seksual terbuka, sementara publik baru bereaksi ketika sudah terlambat bagi korban.
Masalah Grooming di Indonesia
Masalahnya, di Indonesia, grooming masih sering disalahpahami. Relasi usia yang timpang dinormalisasi sebagai “pacaran tua-muda”. Manipulasi emosional disebut “kedekatan”. Korban bahkan diminta ikut bertanggung jawab atas relasi yang sejak awal tidak setara. Dalam konteks ini, grooming kerap terlihat seperti green flag, padahal sesungguhnya adalah red flag besar.
Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah mengakui kekerasan seksual non-fisik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) mengakui relasi kuasa dan manipulasi sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak dapat dianggap memberikan persetujuan dalam relasi yang eksploitatif. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum masih sering berfokus pada bukti fisik dan kronologi linear, sementara trauma korban diperlakukan sebagai inkonsistensi.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kota Kupang, persoalan ini diperberat oleh budaya sungkan, relasi hierarkis yang kuat, serta kecenderungan lebih cepat mempertanyakan perilaku korban daripada menyelidiki penyalahgunaan kuasa oleh orang dewasa. Anak diajarkan patuh, bukan kritis; diam, bukan bersuara. Ketika kekerasan tidak langsung meninggalkan luka fisik, ia kerap dianggap tidak berbahaya hingga terlambat. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam Broken Strings, luka grooming sering bertahan jauh lebih lama daripada luka fisik, memengaruhi cara korban memandang diri, cinta, dan kepercayaan.
Dari Bertahan ke Tanggung Jawab
Broken Strings ditulis untuk siapa pun yang pernah hidup dalam diam. Untuk mereka yang memikul beban yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Untuk mereka yang bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Aurélie tidak menawarkan akhir yang rapi atau keadilan yang tuntas. Ia justru jujur mengatakan bahwa tidak ada harga yang cukup adil untuk menebus apa yang telah dirampas. Namun di tengah ketidakadilan itu, ia menegaskan satu hal: bertahan saja sudah merupakan bukti kekuatan.
Buku ini mengingatkan kita bahwa kebingungan korban bukan tanda kelemahan, melainkan dampak dari manipulasi yang sistematis. Bahwa merasa bersalah, merasa “ikut bertanggung jawab”, bahkan membela pelaku, adalah bagian dari luka yang diciptakan grooming itu sendiri. Dan bahwa penyembuhan tidak selalu berarti melupakan, tetapi sering kali dimulai dari memaafkan diri sendiri karena apa pun yang dilakukan demi bertahan hidup.
Namun buku ini juga mengajukan tuntutan moral kepada kita semua. Jika kisah Aurélie ditulis agar satu gadis saja tidak melangkah ke badai yang sama, maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa korban tidak melapor?”, melainkan: apa yang sedang dan sudah kita lakukan agar anak-anak tidak perlu melewati badai itu sendirian?
Kasus di Kupang menunjukkan bahwa grooming bukan cerita masa lalu atau tragedi jauh di luar sana. Ia terjadi di ruang publik, di kota kita, pada anak yang seharusnya dilindungi. Grooming tidak akan berhenti hanya dengan keberanian penyintas untuk bersuara. Ia hanya bisa dihentikan jika masyarakat bersedia percaya, negara bersedia melindungi tanpa syarat, dan sistem hukum berhenti mencurigai luka yang tidak berdarah.
Seperti yang ditulis Aurélie dalam surat untuk dirinya yang lebih muda, gadis kecil yang dulu menangis diam-diam itulah yang sesungguhnya telah menyelamatkan hidupnya. Dan mungkin, dengan membaca dan berani membicarakan kisah ini, kita sedang membantu menyelamatkan gadis-gadis lain yang hari ini masih hidup dalam kebingungan, masih menunggu seseorang mengatakan: kamu tidak terlihat, kamu tidak rusak, dan kamu pantas hidup tanpa takut. Buku ini untuk mereka. Dan opini ini, seharusnya, juga.